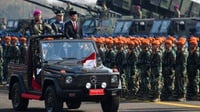tirto.id - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan oleh pemerintah karena ideologinya bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah. Sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa perguruan tinggi yang diduga mendukung organisasi tersebut diperiksa dan terancam terkena sanksi.
Sebagai contoh, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memanggil tiga orang tenaga pengajarnya karena diduga mendukung organisasi ini.
“Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak langsung terlibat dengan elemen-elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
Bersih-bersih di kalangan PNS yang terkait organisasi terlarang bukan yang pertama kali. Pasca-peristiwa 1965, kebijakan serupa dilakukan juga oleh Orde Baru, bahkan dengan cara yang lebih masif dan luas. Orang-orang yang dituduh terlibat PKI dan simpatisannya dihabisi. Para mantan tahanan politik yang lolos dari pembunuhan diawasi ketat. Sementara keturunan dan sanak saudaranya tidak diizinkan menjadi PNS dan aparat TNI/POLRI.
Pemerintah Orde Baru menggulirkan istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” untuk menyaring calon PNS dan TNI/POLRI, juga untuk membersihkan aparatur negara yang kemungkinan sanak saudaranya terlibat PKI dan organisasi pendukungnya.
Hersri Setiawan dalam Kamus Gestok (2003) menjelaskan bahwa istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” diciptakan Orde Baru pasca-peristiwa G30S, terutama setelah terjadi kasus Blitar Selatan pada tahun 1968, yaitu pembersihan sisa-sisa PKI dan simpatisannya lewat Operasi Trisula.
“[Istilah ini] sejatinya merupakan metode manuver politik, untuk meredam setiap gejala gerakan yang menentang rezim, yang semakin dirasa ancamannya sejak 1968 itu,” tulisnya.
Ia menambahkan bahwa pasca-peristiwa 1965 yang berdarah-darah, Orde Baru memang rajin memproduksi istilah-istilah yang diuar-uarkan kepada masyarakat untuk mengeksploitasi kejadian tersebut, seperti “Bahaya Laten Komunis”, “Pancasila Sakti”, “ABRI Penyelamat Pancasila”, dan sebagainya.
“Istilah ‘bersih diri’ mendedahkan bahwa para bekas tapol G30S dan mereka yang berindikasi terlibat pada PKI dan atau ormas-ormasnya, di mata penguasa rezim Orde Baru sebagai orang-orang yang ‘kotor lingkungan’”, ujarnya.
Sementara itu, sasaran istilah “bersih lingkungan”, menurut Hersri, ditujukan pada sanak keluarga eks-tapol tersebut. Luas cakupan kaitannya sejauh tiga generasi, dalam hubungan sanak keluarga horisontal dan vertikal. Yang dimaksud dengan hubungan horisontal ialah: saudara, istri, mertua, menantu, kawan dekat; dan hubungan vertikal ialah: ayah-ibu, anak, dan cucu.
Jejak kebijakan Orde Baru yang diberlakukan selama masa pemerintahannya diterapkan secara sistematis dengan, misalnya, mengembangkan kurikulum anti-komunisme untuk sekolah dan perguruan tinggi.
“Siapa pun yang ingin menjadi PNS atau ingin menjadi pejabat negara harus melalui screening oleh aparat militer untuk memastikan bahwa ia tidak terkait dengan PKI. Banyak anggota keluarga atau keturunan komunis kehilangan hak mereka sebagai warga negara,” tulis Saiful Mujani dalam Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru (2007).
Keterangan serupa diwedarkan oleh Kasiyanto Kasemin dalam Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS/XXV/1966 (2003). Dalam catatannya, pasca-G30S, pemerintah Orde Baru setidaknya melakukan 5 hal yang menjadi acuan mereka untuk memberangus PKI sampai ke akar-akarnya.
Pertama, rakyat hanya dikenalkan pada satu versi sejarah yang terus didaur ulang bahwa peristiwa G30S didalangi PKI. Kedua, semua orang yang ingin diakui sebagai orang baik diwajibkan mendapatkan surat keterangan bebas G30S. Ketiga, memberlakukan politik diskriminasi kepada orang-orang yang terlibat G30S dengan memberikan tanda ET (Eks-Tapol) pada kartu identitasnya.
Keempat, memberlakukan surat keterangan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” melalui mekanisme penelitian khusus. Dan kelima, memberlakukan ketetapan (Tap) MPRS/XXV/1966, yang melarang ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.
“Bahkan tidak itu saja, rezim Orde Baru juga tidak toleran terhadap paham-paham lain, kecuali satu azas tunggal Pancasila,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Baskara T. Wardaya dalam Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto (2007), pembersihan instansi-instansi negeri maupun swasta dari orang-orang yang diduga memiliki kaitan dengan PKI menunjukkan dua hal dalam diri rezim Orde Baru.
Pertama, mereka seakan mengakui gagalnya pemerintahan yang didukung militer tersebut dalam membasmi PKI pada era 1960-an, dan yang kedua sebagai bagian dari taktik Orde Baru mengontrol masyarakat.
“Langkah-langkah yang diambil ini tentu saja tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum mereka yang oleh Soeharto dan para pendukungnya dianggap bersalah, melainkan juga untuk memberi ‘peringatan’ sekaligus ‘pelajaran’ bagi mereka yang diam-diam berniat mengkritik pemerintah,” ujar Baskara T. Wardaya dalam bukunya yang lain, Bung Karno Menggugat: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 hingga G30S (2008).
Kebijakan Orde Baru yang diskriminatif dan penuh stigma terhadap orang-orang yang diduga terlibat, keturunan, atau mempunyai sanak saudara yang terlibat PKI, membuat ribuan orang kehilangan haknya.
Seorang ibu tua di Tasikmalaya, seperti dituturkan Pepih Nugraha dalam Ibu Pertiwi Memanggilmu Pulang (2013), berkeluh kesah karena ia menjadi korban kebijakan sapu bersih yang dilakukan Orde Baru.
Pepih memanggilnya Emak. Di KTP Emak tertera ET (Eks Tapol). Suaminya diduga sebagai anggota aktif PKI dan ia terimbas. Sekali waktu, ia dan suaminya memang menghadiri sebuah acara kesenian yang diadakan oleh PKI, dari situlah pemerintah menuduh bahwa Emak dan suaminya adalah anggota PKI.
“Kesalahan Emak dahulu karena ikut-ikutan pesta rakyat yang ternyata diselenggarakan oleh PKI. Emak dan almarhum suami Emak bukan anggota PKI. Kartu anggota partai pun Emak tak punya. Namun…, sudahlah,” ujarnya seperti dikutip Pepih.
Setelah suaminya meninggal, Emak hidup ditopang oleh anak-anaknya yang berdagang rokok dan sayur-sayuran. Dengan label ET di KTP, Emak terpidana sepanjang hidupnya. Ia juga tentu tak bisa mengharapkan anak-anaknya menjadi PNS, kecuali hanya berangan-angan, dan hanya sebatas angan-angan.

September 1998, saat reformasi masih berusia amat muda, di Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat, Zai Ahmad Zain—koordinator kelompok yang menamakan diri Reformasi Pemerintah Lima Puluh Koto (Repelita) diperiksa polisi karena dianggap telah menyerang Bupati kabupaten tersebut saat berunjuk rasa dengan tuduhan tidak “bersih lingkungan”.
Ibu mertua Aziz Haily (Bupati Lima Puluh Koto) dituduh terlibat Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) yang berafiliasi dengan PKI. Oleh karena itu, Zai menuntut Aziz Haily untuk berhenti dari jabatannya. Menurut Zai, bupati itu lolos dari screening karena memanipulasi data pribadinya.
“Tanda nomor OT (organisasi terlarang) Nisam (mertua Aziz Haily) ada sama komandan Kodim. Saya bertanggungjawab atas keterangan saya ini,” ujar Zai.
Tak terima atas tuduhan tersebut, Aziz Haily segera melaporkan Zai ke pihak kepolisian. Ernita, istri Aziz Haily juga dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Tuduhan Zai itu sungguh menyakitkan. Masa seenaknya ibu saya ditukar dengan orang lain,” ujarnya.
Di Jawa Timur, tahun 2003, Soeryono seorang tamtama polisi menggugat Kapolri dan Kapolda Jawa Timur. Tindakan berani ini dilatari oleh tudingan bahwa dirinya tidak “bersih lingkungan” karena mertuanya dituduh terlibat G30S.
Tuduhan yang menimpa dirinya bermula sejak 1991, tapi tak ada bukti. Pada 1994, ia mengajukan kenaikan pangkat dan disetujui oleh Kapolri karena dirinya dianggap memenuhi syarat. Namun, setahun berikutnya harapan ia pupus. Intelijen Polda Jawa Timur mencabut surat keterangan bebas dari G30S milik Soeryono.
Ia lalu menempuh langkah hukum. Juni 2003, perjuangannya mulai menuai hasil. Pangkatnya naik setingkat jadi brigadir. Namun, Soeryono tak puas dengan kenaikan pangkat itu. Menurutnya, jika saja dirinya tak terganjal kasus ini, ia sudah berpangkat empat tingkat lebih tinggi yakni ajun inspektur polisi.
“Saya bukan mencari pangkat, melainkan kehormatan,” kata Soeryono.
Bagaimana Sekarang?
Hari ini keturunan anggota PKI telah ada yang menjadi anggota DPR. Ribka Tjiptaning, anggota parlemen dari PDIP adalah anak Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro, salah satu anggota PKI. Ribka yang menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI (2002) terpilih menjadi anggota DPR dalam dua periode.
Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Mahfud MD menunjukkan bahwa hak sipil keturunan orang-orang (yang dianggap) PKI sudah pulih. “Keturunan PKI sekarang sudah bisa kerja di kantor-kantor dan tidak diganggu-ganggu. Orang mau kerja enggak dilihat KTP-mu apa. Sekarang sudah bisa jadi [anggota] DPR, pegawai negeri dan sebagainya,” kata Mahfud MD.
Di sisi lain, dalam rangka memulihkan hak yang tercerabut di masa lalu, ada pula imbauan untuk melakukan pengungkapan kebenaran, pengadilan HAM, dan dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Misalnya pada kasus pembantaian dan penghukuman tanpa-peradilan setelah tragedi G30S serta kasus-kasus pelanggaran HAM lain seperti tragedi Talangsari.
Editor: Maulida Sri Handayani