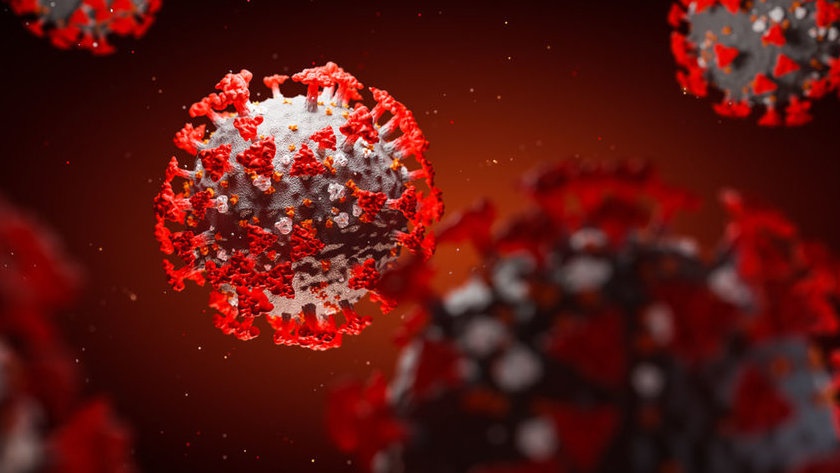tirto.id - Taiwan, sebuah pulau di Asia Timur yang luasnya 35.801 kilometer persegi, semestinya jadi tempat subur penyebaran Corona COVID-19. Alasannya sederhana: 400 ribu dari 23 juta warganya tinggal di Cina daratan, negara tempat pandemi ini pertama kali merebak. Sebanyak 850 ribu warga Taiwan juga tinggal di sana. Jarak antara kedua pulau ini pun hanya 130 kilometer, lebih jauh dari Jakarta-Bandung yang jaraknya 151 kilometer.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Per Selasa (24/3/2020) lalu, Pusat Pengendalian Wabah Terpadu (CECC) Taiwan menyebut ada 215 kasus positif COVID-19. Pada hari yang sama, menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), jumlah kasus positif COVID-19 di Cina mencapai 81 ribu lebih, Korea Selatan 9 ribu lebih, Italia 63 ribu lebih, dan Iran sebanyak 23 ribu lebih.
Angka kesembuhan di Taiwan juga relatif tinggi dibanding angka kematian. Per 24 Maret, ada 29 orang sembuh dan 2 meninggal. Bandingkan dengan Indonesia: per 25 Maret, dari 790 kasus, ada 58 orang meninggal sementara yang sembuh 31.
Lalu, apa sebenarnya kunci sukses Taiwan mengontrol pandemi ini? Yang jelas, semua tidak terjadi secara kebetulan, apalagi hanya mengandalkan doa.
Jason Wang, Direktur Pusat Kebijakan, Hasil, dan Pencegahan Penyakit dari Universitas Stanford, punya jawaban yang bisa merangkum semua: “Sebelum orang lain bilang, ‘siap, siaga, mulai,’ mereka sudah lebih dulu mempersiapkan diri. Jadi, pas orang lain bilang, ‘mulai,’ mereka sudah berlari.”
Kewaspadaan tinggi dan gerak cepat jadi ajian jitu pemerintah Taiwan mengontrol penyebaran liar wabah ini. Wang memberi contoh bagaimana itu diimplementasikan: “Mereka secepat mungkin mendatangi pesawat yang berisi orang-orang dari Wuhan. Sebelum turun, mereka mengecek gejala orang-orang itu. Mereka sangat waspada dalam mendeteksi kemungkinan infeksi yang masuk.”
Sikap seperti ini jelas tak muncul tiba-tiba. Mengutip TIME, Taiwan “siap ketika wabah di Wuhan terjadi” karena mereka belajar dari “pengalaman SARS pada tahun 2003”.
Apa yang mereka lakukan setelah SARS surut adalah mendirikan National Health Command Center (NHCC) dengan segala sistem dan sumber daya yang dipersiapkan dengan matang. Lembaga inilah yang punya peran besar mengatasi persebaran liar COVID-19. Di lembaga ini pula Pusat Pengendalian Wabah Terpadu (CECC), yang diaktifkan kembali pada 20 Januari 2020, menginduk.
CECC memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang membuat pemerintah bisa bergerak cepat untuk menangani wabah.
CECC yang dipandu Menteri Kesehatan Shih-cung telah mengimplementasikan 124 tindakan dalam lima minggu pertama saat outbreak, kata Jason Wang pada ABC, 13 Maret lalu. Tindakan itu di antaranya: mengeluarkan larangan perjalanan, mengalokasikan sumber daya untuk produksi 4 juta masker wajah per hari, juga menertibkan penyebaran informasi keliru yang disengaja.
Larangan perjalanan terkini dikeluarkan pada 18 Maret lalu. Mereka memutuskan menutup pintu masuk bagi orang asing sebagai langkah lanjutan menekan COVID-19 di dalam negeri karena makin banyaknya angka imported cases. 20 kasus terakhir memang merupakan penularan dari luar. Para pembawa virus masuk ke Taiwan antara 13-22 Maret, dan menunjukkan gejala sejak 9-23 Maret.
Negara yang mereka kunjungi sebelum masuk ke Taiwan di antaranya adalah Belgia, Bulgaria, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Thailand, Turki, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, termasuk Indonesia.
Warga juga diminta menceritakan detail perjalanan kepada otoritas terkait. Data orang Taiwan yang berlibur ke luar negeri yang dikantongi pemerintah jadi alat buktinya. Jika tidak jujur, mereka diganjar sanksi.
Sementara untuk masker, selain produksi jutaan lembar dalam sehari, mereka juga mengendalikan distribusinya dalam rangka mengantisipasi kelangkaan, penimbunan, dan permainan harga. Kebijakan itu dimulai 24 Januari lalu, bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor masker medis.
Harga masker dipatok 5 dolar Taiwan atau sekitar Rp2 ribu per lembar. Pembelian dibatasi. Orang dewasa hanya boleh membeli tiga lembar per hari, sedangkan anak-anak lima lembar. Masker tersedia di rumah sakit, supermarket, dan apotek.
Dengan penganggaran yang baik, dalam waktu satu bulan, pemerintah Taiwan juga berhasil menciptakan 60 jalur produksi masker dan meningkatkan angka produksinya menjadi 10 juta lembar per hari.
Untuk mereka yang dikarantina, pemerintah memberikan ganti rugi 1.000 dolar Taiwan atau sekitar Rp 503.900 per hari. Namun, mereka tidak akan dapat menerima insentif jika tidak melapor tepat waktu.
Kemudian, seperti pemerintah Indonesia, pemerintah Taiwan juga menyelenggarakan konferensi pers setiap hari. Bedanya, mereka juga memberikan informasi langsung ke ponsel warga tentang potensi penyebaran virus.
“Kami berpikir hanya ketika informasi transparan, dan orang-orang memiliki pengetahuan medis yang memadai, ketakutan mereka akan berkurang,” kata Juru Bicara Pemerintah Taiwan, Kolas Yotaka kepada NBC News.
Maksimalisasi Teknologi
Selain yang sifatnya konvensional, pemerintah Taiwan juga memanfaatkan betul teknologi. “Mereka juga menggunakan big data,” kata Jason Wang.
Salah satu penerapannya adalah aplikasi live map yang menunjukkan ketersediaan masker di tempat terdekat sesuai waktu sekarang (real time). Peta ini dibuat oleh Audrey Tang, Menteri Digital—sekaligus menteri termuda Taiwan.
Pelacakan riwayat perjalanan seseorang juga menggunakan teknologi, yaitu data program asuransi kesehatan nasional yang diintegrasikan dengan database dari Imigrasi dan Bea Cukai.
Selain itu, dengan data kependudukan sipil dan kartu masuk orang asing, orang-orang berisiko tinggi diidentifikasi dan dikarantina mandiri. Sedangkan penumpang berisiko rendah tetap dipindai dengan kode QR sebelum kedatangan atau kepergian, dan diwajibkan mengisi formulir pernyataan kesehatan.
Pada 18 Februari kemarin, pemerintah memberikan akses riwayat perjalanan pasien ke semua rumah sakit, klinik, dan apotek.
Milo Hsieh, seorang mahasiswa dari Amerika, adalah salah satu orang yang dikarantina mandiri. “Saya tidak diizinkan keluar dari apartemen. Saya tidak diizinkan naik angkutan umum dan harus naik 'taksi karantika' khusus. Seluruh keluarga saya harus dikarantina selama dua minggu. Ini termasuk Biscuit, anjing kami,” katanya menceritakan pengalaman kepada BBC.
Suatu pagi di hari Minggu, ponsel Milo mati. Dalam waktu kurang dari satu jam, empat petugas datang ke apartemennya karena “pemerintah telah kehilangan jejak saya”.
Pemerintah Taiwan memang menggunakan sinyal telepon untuk melacak lokasi seseorang. BBC menggunakan kata 'surveillance' untuk menggambarkan situasi ini, kata yang cenderung berkonotasi negatif tetapi efektif mencegah COVID-19.
Editor: Rio Apinino