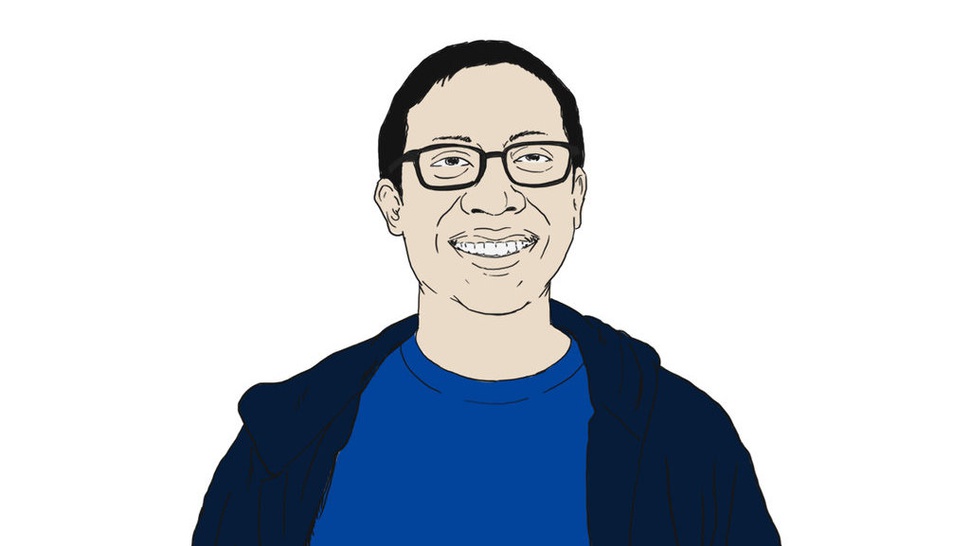tirto.id - Tidak ada yang baru dari tulisan ini. Argumennya pun sederhana: ada struktur ekonomi politik yang lebih berpengaruh ketimbang orang paling berkuasa di negeri ini. Namun, untuk bisa sampai pada kenyataan yang masih banyak disangkal tersebut, perlu kejernihan untuk pelan-pelan mengupas realita yang lebih lawas dari periode kepemimpinan mana pun. Sebab, oligarki sudah ada sebelum presiden saat ini mengawali kiprahnya.
Untuk itu, tulisan ini lebih merupakan ikhtisar atas berbagai inisatif untuk memahami dinamika ekonomi politik di Indonesia, yang menurut beberapa kalangan, teratasi dengan adanya orang baik dalam pusaran kekuasaan. Dari sudut pandang teori sosial, kesimpulan semacam itu jelas sebuah kekeliruan fatal karena mengabaikan faktor kuasa, yang bisa jadi melampaui jangkauan kekuasaan seorang presiden.
Bagi para peneliti sosial yang sudah mempelajari relasi kepemilikan modal dan politik di Indonesia pasca 1998, situasi seperti saat ini sudah bisa diprediksi lantaran polanya yang kerap terulang. Ada benang merah yang terjalin sejak 2000 sampai sekarang dengan tebal tipis yang bervariasi. Dengan kata lain, argumen mengenai oligarki tidak hanya muncul dewasa ini.
Sejak era Suharto, Jeffrey Winters sudah berargumen bahwa kekayaan Indonesia dikuasai segelintir kelompok—sebuah pernyataan yang membuatnya dilarang masuk Indonesia oleh rezim Orde Baru. Di bawah kepemimpinan SBY pun mendiang George Junus Aditjondro bercerita mengenai “Gurita Cikeas”yang sejalan dengantesis oligarki.
Karena memori kolektif kita lemah, ada baiknya beberapa contoh untaian kepentingan segelintir orang di republik ini disebut satu per satu:
- Kasus lumpur Lapindo sejak 2006
- Pasal rokok yang hilang (2009)
- Persekongkolan tambang dan politik sejak 2010
- Reklamasi Teluk Benoa sejak 2012
- Reklamasi Teluk Jakarta sejak 2012
- UU Pilkada (2014)
- Mafia Migas dan kegagalan pembangunan kilang minyak sejak 2014
- Kasus Semen Rembang sejak 2017
- Keterpaksaan impor garam sejak 2017
- Revisi UU KPK (2019)
- UU Cipta Kerja sejak 2019
- UU Minerba (2020)
- Impor Ventilator (2020)
Dari beberapa contoh yang disebut di atas, bisa dilihat bahwa semuanya merupakan sektor ekonomi yang padat modal, berkelindan dengan kepentingan politik serta kuasa, dan sangat dekat dengan kepentingan pengusaha papan atas yang—dalamberbagai bentuk—aktifberelasi dengan dunia politik. Perspektif ini juga membantu memahami mengapa Susi Pudjiastuti—yang kerap melawan kemauan para mafia impor- tidak lagi dipercaya sebagai menteri di periode kedua. Bahkan isu penanganan Covid-19 pun demikian terjerat kepentingan ekonomi politik.
Argumen soal bagaimana politik dan ekonomi berkelindan di tingkat lokal juga sudah didengungkan oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison sejak 2005 dalam Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Di luar itu, ada gugus riset di FISIPOL UGMyang sudah lama meramalkan terhempasnya kedaulatan publik oleh cengkeraman kepentingan penguasa.
Ada pula data yang digunakan Jeffrey Winters untuk memperbaharui argumennya mengenai oligarki pasca-Reformasi. Konon, 40 konglomerat Indonesia secara rerata (1,78 miliar dolar AS) jauh lebih kaya dibandingkan dengan konglomerat di Thailand, Malaysia, Singapur. Tingkat konsentrasi oligarkinya mencapai 6.22, yang menunjukkan betapa jomplangnya penguasaan sumber daya oleh orang terkaya di Indonesia. Mereka inilah yang jadi pemeran utama dalam dokumenter Dandhy Laksono, dan diindikasikan afiliasinya dalam perumusan UU Cipta Kerja dalam sebuah rilis pers.
Jeffry Winters berkesimpulan bahwa kaum oligark cenderung bermanuver di lingkup kebijakan nasional, menyandera sistem hukum dan perundangan demi kepentingannya. Menurut Winters, yang menjadi persoalan bukanlah demokratisasi, melainkan ketidakmampuan kita untuk membangun sistem yang bebas dari patronase (impersonal system) dan mampu membatasi jangkauan oligarki itu terhadap hukum serta legislasi. Dinamika ini tercermin dalam konstelasi politik tingkat nasional.
Fakta bahwa politik di Indonesia sangat mahal dan menjadi lahan intervensi pemilik modal cair sudah diurai dengan baik oleh Burhanuddin Muhtadi dan riset KITLV. Anda salah alamat jika berpandangan bahwa tesis oligarki ini adalah cara pihak ‘asing’ maupun kubu opisisi untuk menjatuhkan kedaulatan rezim saat ini. Ada buku yang seutuhnya ditulis oleh para cendekiawan muda mengenai topik ini.
Cara paling ilmiah untuk masuk pada debat substantif adalah dengan membahas tersanderanya negara dan kebijakan publik di ketigabelas contoh di atas. Idealnya, para teknokrat yang memiliki peran sebagai penasihat dalam lingkaran terdalam bisa menunjukkan hal sebaliknya, sebagaimana sering mereka ungkapkan dalam berbagai forum. Jika memang masalahnya bukan pada sebuah tatanan yang oligarkis, sebaiknya perlihatkan secara transparan kepada publik di mana letak persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Bagi ilmu sosial dan para penelitinya, agenda yang paling jelas adalah menunjukkan dengan rinci dan ketat bagaimana pengaruh kelompok terkaya di Indonesia ini terhadap agenda pembuatan kebijakan baik di tingkat lokal maupun nasional. Elaborasi hegemoninya secara umum dalam agenda pembangunan atau keseharian, mulai dari terbatasnya pilihan perumahan yang ada sampai ke pilihan berita yang kita baca akibat konsentrasi kepemilikan perusahaan. Semua ini terkait erat dengan pembuatan kebijakan publik.
Di luar itu, diskursus publik kita perlu dijernihkan dari kebisingan. Ada tiga hal yang patut diingat di sini. Pertama, sejak pemilu 2014, polarisasi di masyarakat sangat mengkristal. Kehidupan bermasyarakat mengalami politisasi berlebih. Diskursus publik mengalami pembodohan dengan segala bentuk kritik terhadap kebijakan publik dianggap sebagai pembangkangan terhadap pemerintah dan pemimpin mengalami penokohan berlebih. Kedua, berhentilah menganggap bahwa niat baik seorang pemimpin akan menghasilkan kebijakan yang baik jika proses pembuatannya mengabaikan prinsip dan logika untuk kepentingan publik. Ketiga, demokrasi tidak membutuhkan fanatisme. Penokohan berlebihan yang sedang kita saksikan adalah imbas dari populisme yang sejatinya hanya kedok untuk memenangkan kursi dan suara.
Kembali, tesis soal oligarki tidak baru dan bukan dibuat untuk menjatuhkan pemerintahan. Sebaliknya, Kinerja pemerintahan saat ini justru menkonfirmasi bahwa banyak kebijakan publik dibuat lantaran tekanan sistem yang oligarkis tersebut.
Dengan demikian, tersanderanya seorang presiden oleh tatanan politik yang oligarkis bukan merupakan serangan terhadap figur presiden itu sendiri, bukan pula upaya menjatuhkan citranya. Sebaliknya, ada kondisi mendasar yang harus dipahami publik bahwa menaruh harapan kepada seorang figur pemimpin perlu diiringi kemampuan untuk membaca situasi politik yang memungkinkan dia naik panggung. Untuk menyorot betapa pentingnya memahami bagaimana ‘orang baik’ ditaklukkan oleh tatanan yang lebih buas, perlu diakui bahwa semenjak Reformasi tidak ada pemimpin yang bisa seutuhnya menaklukkan kepentingan terselubung lingkaran terdekatnya.
Ini terbukti sampai sekarang.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.