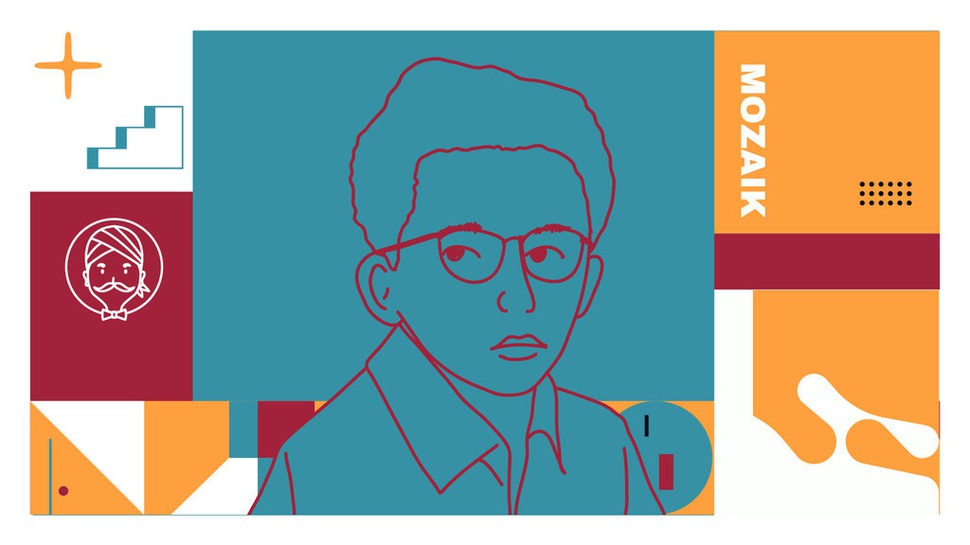tirto.id - Dalam rubrik ‘Obituari’ di Majalah Tempo edisi 9 Juli 2017, Sapardi Djoko Damono menggambarkan Ali Audah, yang meninggal dunia di Bogor, Selasa pagi 20 Juni 2017, tepat 5 tahun yang lalu, sebagai sosok pendiam. Menurutnya Ali “menunjukkan sikap yang tidak pernah berlebihan: cara bicaranya, gerak-geriknya, tatapan matanya, dan pokok pembicaraannya tidak menimbulkan rasa kikuk.”
Ali adalah bintang berkilauan di langit tinggi para penerjemah Indonesia, yang tertatih menyelami bahasa asing untuk dialihbahasakan ke bahasa sendiri. Anak drop out itu telah menempa dirinya dengan begitu keras sehingga dari ketekunannya lahir sejumlah karya terjemahan berkualitas yang dibaca orang banyak.
“Saya hanya menerjemahkan karya-karya besar yang saya nilai bermutu dan bermanfaat,” ujar Ali kepada Budiman S. Hartoyo dari majalah Berita Buku.
Ali terutama dikenal sebagai penerjemah karya-karya berbahasa Arab, seperti biografi Nabi Muhammad SAW karya M. Husain Haekal dan biografi Khulafaur Rasyidin karya penulis yang sama. Ia juga menerjemahkan karya Hamid G. Al-Sahar (Suasana Bergema), Mustafa Hallaj (Murka), Yahya Hakki (Lampu Minyak Ibnu Hisyam), Andre Gide (Theseus), Stefan Zweig (Marie Antoinette), dan lain-lain.
“Karya paling mengesankan adalah terjemahan Abdullah Yusuf Ali, The Holy Quran (1934). Di Indonesia, karya Abdullah diterjemahkan Ali Audah dan diterbitkan oleh Pustaka Firdaus. Laku keras,” tulis Gatra. Karya ini diberi judul: Qur’an, Terjemahan dan Tafsirnya.
Ali lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada 24 Juli 1924. Ia mengenyam pendidikan formal hanya sampai madrasah ibtidaiah alias sekolah dasar. Itu pun tak selesai. Ia badung dan kerap membolos sehingga gurunya sempat mengerangkengnya. Setelah itu, Ali tak lagi bersekolah sampai tua, bahkan sampai hayatnya pungkas.
Baginya, masa bocah adalah surga bermain yang tak boleh diganggu sekolah yang membosankan. Berlama-lama duduk di kelas membuatnya hampir senewen. Maka ia memilih bermain layang-layang, gundu, atau mandi di kali.
“Saya belajar membaca dan menulis dengan mencoret-coret huruf di tanah sambil main gundu,” kata Ali.
Meski kelakuannya bikin jengkel guru, tapi sesungguhnya ia seorang pembelajar yang keras. Ali belajar secara otodidak. Ia pembaca buku yang rakus. Ia pernah diberi uang oleh orang tuanya untuk membeli baju karena yang ada telah kumal dan sobek-sobek. Namun, di pasar, ia malah berbelanja buku.
Sekali waktu, saudaranya yang banyak membaca sastra Arab berkata pada Ali bahwa khazanah kesusastraan Arab memiliki kisah bagus-bagus. Maka, saat saudaranya tinggal di Arab, ia minta dikirimi buku-buku cerita dari jazirah itu.
Banyak orang bertanya butuh berapa lama Ali menguasai bahasa-bahasa tersebut sementara ia tak lagi belajar di sekolah. Ali menjawabnya, “tak bisa dihitung.” Meski singkat, jawabannya jelas menyiratkan kerja keras yang panjang dan tak main-main.
Emha Ainun Nadjib pernah menulis, “Hari ini kita bersama-sama menundukkan dan membungkukkan badan di hadapan beliau, Bapak Ali Audah. Saya pribadi, kalau boleh jujur mempraktikkannya, tidak akan menundukkan wajah, melainkan menutupi wajah, karena rasa malu yang mendalam kepada beliau.”
Meski terkesan dilebih-lebihkan, tapi kiranya ungkapan itu sah-sah saja dialamatkan kepada Ali yang sepanjang hayatnya “mengimani” terjemahan sebagai sebuah pokok yang rumit, dan ia mengerjakannya penuh dedikasi.
Hal ini sekali lagi disampaikan Ali kepada Sapardi, bahwa kemampuannya menguasai berbagai bahasa asing bukanlah bakat melainkan hasil usaha yang terus-menerus. “Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa untuk menerjemahkan diperlukan bakat. Tidak. Menerjemahkan bisa dilakukan dengan latihan,” ujarnya.
Ali Audah Bicara tentang Terjemahan
Bagi Ali Audah, terjemahan yang baik adalah yang berada di tengah-tengah: tidak verbatim atau harfiah, juga tidak parafrasa atau terlalu bebas. Lebih baik lagi jika gaya si pengarang bisa diambil—meski bagi yang tak paham akan menganggapnya harfiah alias terjemahan plek.
Menurutnya, terjemahan verbatim adalah jenis terjemahan yang buruk karena kerap menghamparkan teks yang justru sulit bahkan tidak dapat dimengerti.
Sementara terjemahan parafrasa adalah bentuk ketidakberdayaan si penerjemah. Ia dianggap menuliskan pikirannya sendiri karena tidak bisa menangkap pikiran sang pengarang, pun tidak mampu menangkap bahasanya.
“Kalau terjemahan itu [kita] cocokkan dengan aslinya, tidak bisa dilacak. Penerjemah bikin kalimat sendiri, paragraf sendiri, dan seterusnya. Ini sangat berbahaya, karena konsep, pikiran dan gaya—bahkan nuansa pikiran pengarang—tidak bisa ditangkap dan diungkapkan,” terangnya.
Ali mewanti-wanti para penerjemah agar tetap hati-hati dan tidak seenaknya menambal kalimat yang sulit diterjemahkan dengan pikirannya sendiri. Untuk mengatasi kesulitan ini menurutnya si penerjemah mesti menyertakan catatan kaki, misalnya: “Kalimat atau alinea yang ini sulit diterjemahkan, dan inilah terjemahan yang paling mendekati.”
Ali memang amat disiplin dalam menerjemahkan berbagai karya, baik fiksi maupun nonfiksi. Baginya, menerjemahkan karya ilmiah dan agama tidak bisa hanya mengandalkan ensiklopedia atau kamus, melainkan harus didukung buku-buku referensi. Begitu pula saat menerjemahkan buku sejarah dan biografi. Tak cukup hanya mengacu pada buku yang diterjemahkan saja, tapi mesti didukung karya dari pengarang lain. Sementara untuk menerjemahkan novel, mesti dilihat pula latar belakang budaya yang ada dalam cerita tersebut.
“Kalau tidak, saya khawatir terjemahan itu meleset. Dia [juga] tidak bisa ingin cepat-cepat selesai menerjemahkan hingga terburu-buru,” ujarnya.
Kadang ia perlu satu sampai dua jam hanya untuk menerjemahkan satu kata atau kalimat agar benar-benar cocok dan pas. Ia mesti mencari, mencocokkan, dan membandingkannya di berbagai kamus, ensiklopedi, atau referensi lain.
“Kalau masih buntu, biasanya saya tinggalkan dulu, lalu saya membaca buku lain,” tambahnya.
Sikap disiplin dan hati-hati itulah yang ia dekap sepanjang hayat sebagai penerjemah. Tak heran jika karyanya bermutu dan memuaskan para pembaca.

Terjemahan Bukan Karya “Kelas Dua”
Sebagian kalangan masih menganggap terjemahan adalah karya minor karena “hanya” mengalihbahasakan sebuah karya. Oleh karena itu ada yang enggan sama sekali membaca terjemahan dan bangga jika membaca langsung karya asli.
“Ada pula orang yang mau membaca karya terjemahan, tapi kalau menulis dan menyebutnya sebagai referensi—untuk catatan kaki atau bibliografi, misalnya—ia menyebutkan karya aslinya. Padahal yang ia baca terjemahannya,” terang Ali Audah.
Untuk soal ini, Ali mengambil sikap tegas: jika menulis menggunakan karya terjemahan, karya itulah yang dicantumkan sebagai kredit, bukan yang asli. Ali berpendapat bahkan kita tidak perlu melihat karya asli jika memang terjemahannya baik.
Menurutnya terjemahan yang baik adalah karya yang setara dengan karya aslinya. Sebuah karya kreatif yang tidak kurang berharga dibanding karya asli. Ia bukanlah karya “kelas dua”.
Salah satu karya terjemahan yang baik itu menurutnya adalah Al-Buasa karya Habib Ibrahim, hasil alih bahasa Les Miserables. Bahkan, saking baiknya karya tersebut, masyarakat tidak tahu sang pengarang aslinya. “Begitu terkenalnya Habib Ibrahim di Mesir sebagai ‘pengarang’ Al-Buasa hingga orang di sana tidak mengenal siapa itu Victor Hugo,” tuturnya.
Memang, tidak hanya Ali yang sadar betapa pentingnya karya terjemahan. Sastrawan pun demikian.
Menurutnya pernah ada satu masa ketika Sutan Takdir Alisjahbana terus-terusan menganjurkan “pengambilalihan” ilmu pengetahuan melalui terjemahan berbagai buku. Sastrawan angkatan Pujangga Baru itu bahkan sempat mengidamkan penerjemahan Encyclopedia Britannica.
Atas semua kontribusinya, tidak heran jika Ali Audah mendapat apresiasi dari banyak orang.
Salah satu yang menaruh takzim kepada penerjemah ini adalah sastrawan Remy Sylado. Dalam buku 90 Tahun Ali Audah yang diterbitkan Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin, Remy mengatakan bahwa ia terkesan pada karya Ali yang bertajuk Konkordansi Qur’an, Panduan Kata dalam Mencari Ayat Qur’an. Sebagai seorang Nasrani yang mempelajari Islam, ia tertolong oleh karya tersebut.
Bagi Remy, Ali adalah seorang “budayawan tulen yang mengagumkan karena ketekunannya di ladang kitabullah.”
Lebih dari itu, Remy mengungkapkan bahwa terjemahan sangat penting dan dibutuhkan bangsa Indonesia untuk melatih berpikir dan merdeka. Di titik inilah posisi Ali yang cakapnya tertib itu tak bisa dipisahkan dari riwayat penerjemahan karya asing ke dalam bahasa Indonesia.
“Bagi bangsa yang awet hidup dalam tradisi cangkem—bayangkan, di Indonesia berlaku istilah ‘sastra lisan’, padahal yang namanya ‘sastra’ dalam bahasa Kawi, kata Zoetmulder, adalah ‘tulisan’—karya-karya luar yang demikian perkasa berdiri di atas tradisi tulis, karuan dirasa wajib untuk diterjemahkan,” ujar Remy.
====================
Artikel ini terbit pertama kali pada 18 Mei 2018 dengan judul yang sama. Redaksi melakukan penyuntingan ulang dan menayangkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan & Rio Apinino