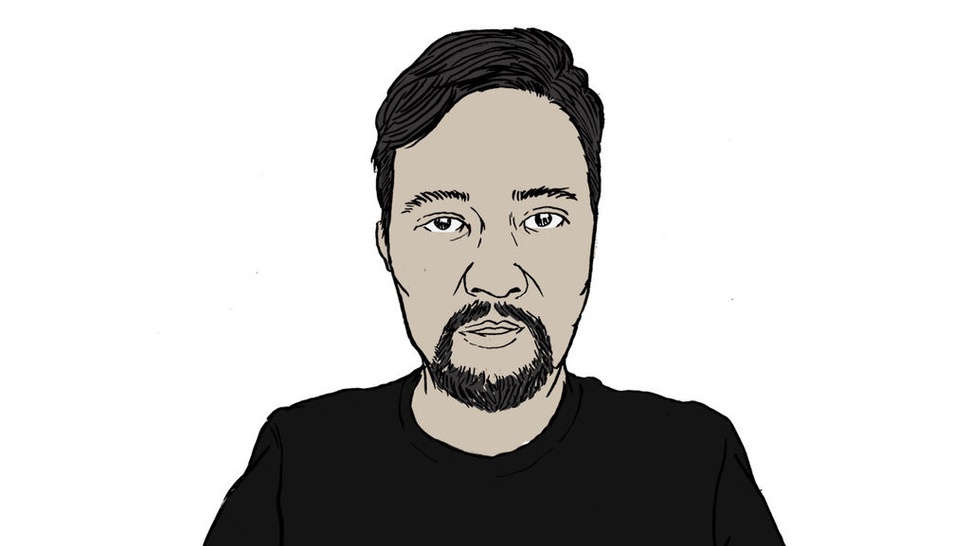tirto.id - Relatif tidak ada yang benar-benar baru dari May Day 2019 di Jakarta, kecuali bahwa aparat kepolisian semakin cerdik mensegregasi serikat buruh yang turun ke jalan. Jika beberapa tahun lalu semuanya bisa mencapai Ring 1 Istana Negara (jika memang tujuan akhirnya ke sana), maka setidaknya sejak 2017 mereka tak bisa lagi mencapai titik itu.
Bahkan pada May Day terakhir, Rabu (1/5/2019), barisan buruh mentok di patung kuda, padahal setahun sebelumnya bisa lebih jauh.
Tahun ini polisi berjaga di dua titik (Bunderan HI dan Patung Kuda). Dengan pengecualian KSPI-Said Iqbal yang memilih mendengarkan Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno, penjagaan ini membuat dua kelompok buruh yang titik kumpulnya berbeda tak bisa bergabung. Masing-masing tertahan, meski kemudian barikade polisi di Bunderan HI bisa dijebol pada siang jelang sore.
Ini belum termasuk taktik lain yang dirancang agar para buruh tak turun ke jalan. Tahun lalu, Menteri Tenaga Kerja DKI Hanif Dhakiri—bekas angota partai terlarang era Orde Baru, PRD—menggelar ‘May Day Festival’. Isi acaranya: latihan membuat kue, kompetisi band, futsal, hingga mengaji bersama.
Tahun ini Polres Bekasi bahkan menggelar acara yang menyediakan hadiah utama mobil.
Memang tak pernah ada penelitian atau data resmi yang membuktikan apakah cara-cara tersebut membuat jumlah massa berkurang atau tidak. Namun ini bisa diperkirakan dari jumlah buruh (baik kerah putih atau biru) yang berserikat. Sebab, setidaknya di Jakarta, sangat jarang buruh yang tak berserikat mau berdemonstrasi saat May Day. (Bagaimana mau ikut kalau yang lain pakai seragam serikat yang logonya seram-seram itu? Belum apa-apa pasti sudah diteriaki “intel”).
Berdasarkan data kementeriannya Hanif, mereka yang berserikat pada 2017 hanya 2,7 juta orang, kontras dibanding jumlah angkatan kerja yang diperkirakan mencapai 131,55 juta pada tahun yang sama. Sebagai pembanding, 10 tahun sebelumnya, yang berserikat mencapai 3,4 juta orang.
Ada dua kemungkinan penyebab, selain yang di awal tadi sudah disebutkan: pertama, bahwa buruh di Indonesia sudah semakin sejahtera sehingga tak butuh lagi demo; kedua, ada yang salah dari serikat itu sendiri.
Kemungkinan pertama adalah jawaban konyol. Sistem ekonomi-politik saat ini justru membuat buruh semakin rentan (precarious) dan lemah. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, misalnya, membuat buruh tak punya lagi daya tawar untuk menentukan besaran upah, sebab semua telah dikalkulasikan sedemikian rupa dengan hitung-hitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi semata. Pekerja Indonesia juga, terutama yang kontrak dan alihdaya (outsourcing), biasanya bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dengan pendapatan yang tak pasti.
Jawaban kedua lebih masuk akal: bahwa ada yang salah dari serikat itu sendiri.
Musuh dalam Selimut: Elite Serikat
Selalu ada reaksi dari tiap aksi. Begitu pun dengan demonstrasi buruh. Pada 2008 lalu, ketika Aliansi Buruh Menggugat (gabungan serikat-serikat buruh) sedang besar-besarnya, untuk pertama kalinya para politikus—meminjam istilah Hilmar Farid—“bermain mata” dengan para buruh. Mereka (salah satunya politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid) menyelenggarakan acara bertajuk May Day Fiesta—sesuatu yang kini sudah jamak—di Istora Senayan, yang pada dasarnya tak lebih sebagai acara hura-hura.
Sedikit banyak acara tersebut memecah para buruh. Kabarnya saat itu ada kira-kira 20 ribu buruh turut serta.
Apa yang terjadi pada 2014 lebih menggelikan. Serikat buruh (atau lebih tepatnya: elite serikat) terseret ke dalam arus politik para pemilik modal (dan terus berlanjut hingga sekarang). Beberapa dari mereka menyatakan dukungan terbuka kepada politikus yang hendak mengambilalih kursi RI-1 dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah berkuasa sejak 2004: antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Sejak saat itulah serikat buruh tak sama lagi.
‘Menitipkan nasib’—dan lantas membayarnya dengan janji ‘suara’—ke politikus yang jelas-jelas bukan berasal dari kelas pekerja dan bahkan turut serta membuat nasib buruh seperti sekarang adalah hal konyol, meski mereka mengatakan itu taktik belaka. Sebab, serikat buruh awalnya adalah alat perjuangan kelas buruh. Dia selalu mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelas buruh yang selalu bertentangan dengan para pemilik modal.
Atas dasar itu pula orang-orang bergabung ke serikat. Mereka hendak mencari keselamatan, atau minimal kawan senasib-sepenanggungan.
Tak ada pihak lain yang patut ditunjuk hidungnya selain elite serikat itu sendiri. Saya berani bertaruh, elite serikat-serikat yang menyatakan dukungan untuk politikus itu tak pernah mendengar seluruh aspirasi anggotanya untuk keputusan sepenting itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan serikat di Indonesia tidak demokratis. Hampir semua keputusan strategis ada di tangah segelintir elite, sementara para anggotanya pasif menerima keputusan apa pun. Termasuk, misalnya, berapa upah yang dipotong untuk iuran bulanan atau persenan dari uang pesangon jika advokasi berhasil.
Elite-elite ini jelas diuntungkan dengan posisinya sebagai “raja kecil” itu. Saya tidak mengatakan ada keuntungan materiil, tapi satu hal yang pasti diperoleh adalah reputasi sebagai pimpinan organisasi berjumlah sekian ratus ribu anggota. Alasan apa lagi yang masuk akal hingga Joko Widodo mau mengundang mereka ke Istana Bogor jika bukan karena itu? (Mereka jelas bukan Youtuber…).
Jika saya anggota serikat yang menyatakan dukungan untuk politikus tertentu, yang itu kebetulan berbeda dari pilihan politik saya, maka saya akan berpikir lagi tentang keberadaan saya di serikat itu. Toh bukan hal sulit untuk pindah ke serikat lain agar tetap ada yang melindungi jika ada masalah ketenagakerjaan yang saya alami.
Karena alasan itu pula saya menduga kaderisasi di serikat macet (atau sengaja dibuat begitu, entah). Pimpinan serikat di tingkat pusat—sependek yang saya tahu dari enam konfederasi besar di Indonesia—tak pernah berganti mesti telah memimpin bertahun-tahun. Siapa sih yang mau segala privilese itu hilang karena kepemimpinannya dialihkan ke orang lain? Soeharto saja mati-matian mempertahankan jabatan presiden selama puluhan tahun.
Ringkasnya, bagi saya pimpinan serikat model begini (baca: oligark serikat) adalah musuh dalam selimut yang membuat anggota-anggota lain tak berkembang.
Mendengar Cerita-Cerita Kecil
Saya ikut-ikutan nimbrung May Day sudah tujuh kali. Dan selama itu pula para orator di mobil komando menarasikan hal yang sama, yang sifatnya sloganistik tanpa penjelasan apa-apa lagi seperti “lawan kapitalisme/neoliberalisme”, “hajar imperialisme”, “buruh bersatu tak bisa dikalahkan/buruh berkuasa rakyat sejahtera,” hingga “sosialisme jalan sejati pembebasan manusia.” (jangan lupa: nyanyikan Internasionale di akhir demo lalu nyalakan flare).
Memang tak ada yang salah dari itu, tapi terus-terusan mengulanginya juga bagi saya tidak tepat.
Yang lenyap padahal semestinya ada dari May Day tiap tahun adalah suara-suara kelompok paling bawah di serikat: anggota biasa. Ini penting karena semuanya sudah direbut dari kelas pekerja, termasuk narasi keseharian mereka, baik oleh pengusaha atau elite serikat. Narasi keseharian itu termasuk bagaimana mereka bertahan hidup di rejim upah murah; bagaimana menindasnya para mandor di pabrik; betapa tidak sehatnya kontrakan dan makanan mereka; sulitnya mengejar target produksi; kenapa mereka akhirnya memutuskan buat berserikat; mustahilnya mereka membeli barang yang mereka produksi sendiri; dan lain-lain.
Apakah ini mungkin? Jelas mungkin. Dan sudah ada buktinya. Tengok saja buku Buruh Menuliskan Perlawanannya terbitan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). Buruh-buruh biasa ini bukan hanya bicara, tapi menuliskan pengalamannya secara apik. Buku ini, seperti dikatakan Jafar Suryomenggolo, membuktikan bahwa “buruh tidak lagi bergantung pada kata-kata para sarjana atau penggiat LSM.”
Selain mengembalikan narasi pekerja, cerita-cerita kecil ini juga penting bukan agar orang kasihan, tapi supaya mereka tahu apa yang sesungguhnya dialami para buruh. Seringkali ketidaktahuanlah yang memunculkan resistensi. Itu mungkin kenapa saban buruh berdemonstrasi, ada saja orang lain yang mencibir. Orang-orang ini sebetulnya juga buruh tapi enggan disebut buruh, termasuk para wartawan dengan pemberitaannya yang kadang berat sebelah.
Mereka bisa jadi hanya tak tahu.
Bagi saya, itulah esensi May Day. May Day yang benar-benar merupakan hari rayanya pekerja, bukan hari para elite serikat memamerkan kemampuan pidato hingga berjam-jam dan membuat para anggota bosan.
Memang ini tak bisa dilakukan serta merta. Ada problem lain yang harus diselesaikan, misalnya pengurus serikat harus memberi ruang bagi anggota biasa atau melatih para anggota untuk biasa berbicara. Ini, lantas, kembali lagi ke poin awal tadi: bagaimana serikat menjadi organisasi yang dikelola secara demokratis dan semua anggota punya kesempatan yang sama untuk maju.
Tanpa itu May Day hanya akan jadi rutinitas tahunan yang lama-lama akan membosankan.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.